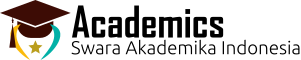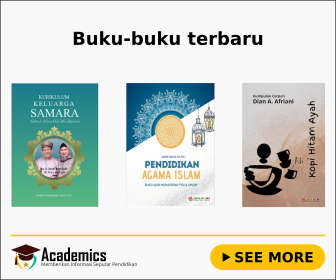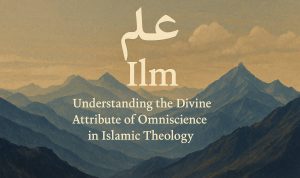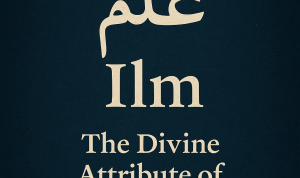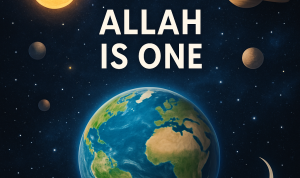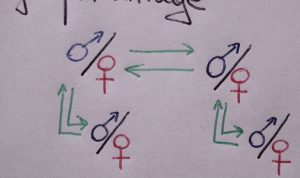ACADEMICS.web.id – “Lo percaya Tuhan itu ada?” Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi di baliknya tersimpan perdebatan panjang yang telah menyalakan api filsafat, memicu perang ide, bahkan mengguncang peradaban. Pertanyaan itu pula yang menjadi jantung dari apa yang kita sebut hari ini dengan istilah ateisme, diderivasi dari bahasa Yunani atheos.
Secara bahasa, kata atheos dalam Yunani berarti “tanpa Tuhan”. Awalnya sederhana, istilah ini ditujukan bagi mereka yang tidak mengakui ketuhanan kelompok lain sebagaimana orang-orang Yunani menyebut kaum Kristen di masa awal, “mereka itu ateis, karena tidak percaya pada dewa-dewi kami.” Artinya, ateis hanya merujuk pada perbedaan konsep ketuhanan semata dimana ketika saya tidak mengakui tuhan anda, maka saya ateis menurut anda dan demikian juga sebaliknya, anda ateis bagi saya. Kemudian, istilah ateis hari ini mengalami pergeseran persepsi dimana ia dilekatkan pada orang yang sama sekali tidak percaya kepada Tuhan.Sejarah memang doyan bermain terbalik.
Namun ateisme tidak sekadar menolak keberadaan Tuhan. Ia bisa jadi berbentuk gugatan intelektual, pemberontakan spiritual, dan kadang, kekecewaan eksistensial. Ada yang menolak Tuhan karena melihat penderitaan dunia, “Jika Tuhan Maha Kasih, kok anak kecil itu harus mati kelaparan?” Ada yang menolak karena merasa akalnya sudah cukup, “Apa artinya keberadaan Tuhan kalau segala sesuatu bisa dijelaskan dengan sains?” Ada pula yang menolak karena merasa Tuhan membatasi kebebasannya, “Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram… kagak bebas kita.”
Jika diringkas, ateisme adalah puncak dari rasa percaya diri manusia yang berlebihan terhadap akalnya. Di sinilah bentangan paradoksnya: akal yang diciptakan oleh Tuhan, justru digunakan untuk menolak keberadaan Tuhan.
Sejarah mencatat bahwa ateisme bukanlah anak kandung abad modern. Ia sudah ada sejak zaman Yunani kuno, di mana para filsuf seperti Epikuros dan Demokritos mencoba menjelaskan alam tanpa melibatkan campur tangan dewa. Baru kemudian ateisme menemukan panggung besarnya pada abad ke-17 dan ke-18, ketika Eropa mengguncang dirinya sendiri melalui zaman Pencerahan (Enlightenment).
Bayangkan sebuah peradaban yang lama hidup di bawah bayang-bayang gereja, tiba-tiba disodorkan ide bahwa manusia bisa hidup tanpa Tuhan. Gereja yang dulu memegang kunci kebenaran mulai retak karena perang internal antara Katolik dan Protestan. Dari sanalah lahir paham deisme—percaya Tuhan ada, tapi tidak ikut campur dalam urusan dunia. Setelah itu, satu langkah lagi menuju ateisme hanyalah soal waktu.
Baron d’Holbach, seorang bangsawan Prancis yang nekat menulis The System of Nature, berkata lantang bahwa semesta bekerja dengan mekanismenya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Ia bahkan menyebut agama sebagai tiran yang menakuti manusia dengan surga dan neraka agar tunduk. Baginya, manusia baru akan tercerahkan jika berani membebaskan diri dari bayang-bayang Tuhan.
“Cukup, Holbach… cukup…!”
Kalimat itu mungkin keluar dari hati siapa pun yang masih punya rasa takut kepada yang Maha Kuasa. Tapi begitulah semangat zaman saat itu dikala akal sedang di atas singgasana, iman diasingkan ke pojok dengkul.
Lalu datanglah abad ke-19, abad yang memperkenalkan kepada dunia dua “nabi baru” ateisme: Nietzsche dan Sartre.
Nietzsche berteriak lantang: “Tuhan telah mati!”
Ia tidak sedang berbicara tentang kematian literal, tapi tentang hilangnya fungsi Tuhan dalam kesadaran manusia modern. Menurutnya, selama manusia masih percaya pada Tuhan, manusia tidak akan pernah bebas. Maka Tuhan harus “dimatikan”, agar manusia bisa menjadi “superman”, makhluk bebas yang menentukan sendiri nilai dan moralnya.
Tapi ironisnya, ketika Tuhan mati, yang lahir bukan manusia super, melainkan manusia hampa. Karena tanpa Tuhan, arah hidup kehilangan kompasnya.
Sementara itu Sartre melanjutkan semangat yang sama, tapi dengan nada yang lebih filosofis. Ia berkata: “Kalau Tuhan ada, maka manusia tidak bebas.” Bagi Sartre, manusia harus sepenuhnya bebas, bahkan bebas dari Tuhan. Tapi kebebasan tanpa arah itu justru menjadi penjara baru. Sartre sendiri akhirnya mengakui bahwa kebebasan total itu membuat manusia gelisah, cemas, dan kehilangan makna. Kebebasan tanpa nilai hanyalah kehampaan yang diberi nama kemerdekaan.
Pada akhirnya, ateisme bukan sekadar soal percaya atau tidak percaya. Ia adalah cermin bagi manusia yang sedang kehilangan dirinya sendiri. Ketika manusia menjauh dari nilai-nilai ilahiah, ia berusaha menggantikan posisi Tuhan dengan akal, dengan kebebasan, dengan teknologi, dengan ego. Tapi hasilnya sama: kekosongan.
Persoalan ateisme bukan soal logika, melainkan luka spiritual.
Bukan soal ada atau tidak ada Tuhan, melainkan apakah hati manusia masih sanggup merasakan kehadiran-Nya di tengah dunia yang penuh kebisingan ini.
Maka, jika ada yang bertanya:
“Apakah ateisme itu bisa dijelaskan secara ilmiah?”
Jawabannya: bisa.
“Tapi bisakah ateisme menenangkan jiwa manusia?”
Jawabannya: tidak.
Karena yang hilang dari ateisme bukan argumen—melainkan rasa tunduk.
Dan di situlah letak perbedaan paling mendasar antara mereka yang mengangkat akal menjadi Tuhan, dan mereka yang menundukkan akal di hadapan Tuhan.
Wallahu a’lam bi al-shawab.
Sofiandi, Lc., MHI., Ph.D
Guru PAI di Bakti Mulya 400, juga tercatat sebagai Research Fellow di beberapa lembaga seperti Fath Institute for Islamic Research Jakarta, IRDAK Institute of Singapore, Asia-Pacific Journal on Religion and Society, Institute for Southeast Asian Islamic Studies, Islamic Linkage for Southeast Asia, Anggota Dewan Masjid Indonesia, Ketua Dewan Pembina Badan Koordinasi Muballigh Indonesia Prov. Kepri, Anggota ICMI Prov. Kepri, Pembina Ikatan Wartawan Online Indonesia Prov. Kepri, dan aktif menulis mengenai isu-isu pendidikan selain politik, sosial, dan ekonomi.