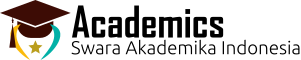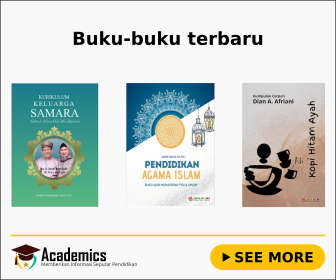ACADEMICS.web.id – Suatu hari, tanpa sengaja telinga saya menangkap perbincangan beberapa anak remaja di sebuah cafe. Salah satunya, dengan santai mencurahkan isi pikiran dengan menyebut bahwa pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) itu “nggak penting-penting amat,” karena yang dihafal cuma syarat-rukun, doa-doa pendek, macam-macam najis, jenis-jenis salat sunah, dan sebagainya. Saya duduk, diam, sambil merenung, menyeruput kopi yang tinggal setengah. Tidak heran, pikir saya, jika kemudian banyak anak-anak muda yang semakin jauh dari nilai-nilai Islam. Mereka merasa sedang belajar agama, padahal nyatanya hanya menghafal informasi tentang agama.
Kalau mau jujur, fenomena ini sejatinya bukan hal baru. Ia seperti penyakit yang sudah lama menggerogoti sistem pendidikan kita, namun dibiarkan begitu saja. Pendidikan Agama Islam hari ini—dengan segala hormat pada guru-guru yang ikhlas mengajar—seakan telah terjebak menjadi “pendidikan tentang agama,” bukan “pendidikan yang menghidupkan agama” dalam jiwa peserta didik. Kita sibuk mentransfer pengetahuan, tapi lupa mentransformasikan kepribadian. Kita giat mengajarkan teks, tapi abai menanamkan konteks.
Bahkan dalam pengamatan saya, cukup banyak siswa yang mendapat nilai sempurna dalam mata pelajaran agama, tapi masih dengan ringan menyontek saat ujian, berkata kasar kepada orang tua, bahkan terjerumus dalam gaya hidup yang jauh dari tuntunan Islam.
Kita patut bertanya, ada apa dengan pendidikan agama kita?
Dalam teori pendidikan Islam klasik, tujuan utama dari belajar agama adalah tazkiyatun nafs—penyucian jiwa. Ini adalah inti dari wahyu. Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya membawa ilmu, tapi juga yuzakkihim—membersihkan hati umat dari penyakit syirik, munafik, dengki, dan keras kepala, yang kemudian outputnya berbentuk makaarimal akhlaq. Dalam Surah al-Jumu’ah ayat 2, disebutkan bahwa Rasulullah SAW membawa tiga misi: membacakan ayat-ayat Allah, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan Kitab dan hikmah. Penyucian jiwa (tazkiyah) didahulukan dari pengajaran ilmu. Kalau di depan mahasiswa, sering saya katakan, inilah kurikulum pendidikan Islam sesungguhnya: Kenalkan siapa Tuhannya – Bersihkan jiwanya – Ajarkan ilmu yang dibutuhkan dalam hidupnya. Tapi, lihatlah apa yang terjadi hari ini: urutan itu kita balik sendiri.
Akhirnya, banyak siswa bisa menjelaskan definisi husnuzhan, tapi tidak bisa mempraktikkannya dalam pergaulan. Mereka tahu hukum ghibah, tapi tak kuasa menahan jari-jarinya dari membully teman lewat media sosial. Pendidikan agama yang didapatkan tidak membekas karena ia hanya menyentuh akal, tidak sampai menembus hati.
Lantas, dimana letak permasalahannya?
Menurut saya, ini semua terletak pada pendekatan pendidikan yang terlalu kognitif dan tekstual. Guru agama dianggap berhasil dan lebih dinilai dari kemampuan menguraikan bab fiqih atau membedakan antara iman dan Islam secara teoritis, ketimbang kemampuannya menginspirasi murid untuk menjadi pribadi yang berakhlak.
Padahal, Rasulullah SAW adalah pendidik par excellence. Beliau tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tapi lebih banyak mendidik dengan keteladanan dan pengalaman. Ia merangkul, bukan menghakimi. Ia memahami proses, bukan memaksa hasil. Ia menanamkan iman, sebelum menuntut amalan.
Pakar pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, jauh-jauh hari telah mengingatkan bahwa pendidikan sejati bukan sekadar transfer ilmu pengetahuan, tetapi “menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.” Pendidikan agama seharusnya tidak sekadar memberi tahu apa itu shalat, tapi menginspirasi mengapa dan bagaimana shalat bisa membentuk karakter taat, disiplin, dan kasih sayang.
Tokoh pendidikan Islam kontemporer, Syed Muhammad Naquib al-Attas, juga menekankan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah adab, yakni penanaman tata nilai yang benar mengenai diri, Tuhan, alam semesta, dan sesama. Ia menyebut, “The loss of adab is the root of all crises in Muslim society.” Maka, ketika pendidikan agama tidak lagi menanamkan adab, yang lahir bukan generasi beriman, melainkan generasi yang hanya mampu menjelaskan rukun iman.
Kemudian, kita harus bagaimana?
Saya kira, kita butuh semacam “revolusi senyap” dalam pendidikan agama Islam. Sebuah pembaruan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan transfer knowledge, tetapi juga transformasi spiritual dan pembinaan karakter. Pendidikan agama harus kembali menjadi pendidikan hati, bukan sekadar pengisian kepala.
Pertama, guru agama harus menjadi inspirator moral, bukan sekadar pengajar materi. Keberhasilan seorang guru agama tidak cukup diukur dari RPP dan silabus, tapi dari seberapa besar ia mampu menggerakkan jiwa muridnya untuk mencintai Islam dan menjadikan Islam sebagai jalan hidup.
Dalam hal ini, Imam Abu Hamid al-Ghazali pernah berkata, “Seorang guru sejati adalah orang yang mengajar dengan amal sebelum perkataan.” Maka, pembinaan karakter sejati hanya mungkin tumbuh dalam ekosistem keteladanan, bukan ceramah kosong.
Kedua, materi pelajaran agama perlu dikontekstualisasikan. Jangan hanya mengajarkan fiqih tayammum, tapi ajarkan juga nilai kesederhanaan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Jangan hanya menjelaskan makna jujur sebagai teori, tapi ajak siswa mempraktikkannya dalam proyek-proyek sosial. Ingat pesan Paulo Freire, tokoh pendidikan kritis dari Brasil: “Education either functions as an instrument to bring about conformity or freedom.” Pendidikan agama seharusnya membebaskan manusia dari kebodohan rohani dan kejumudan moral, bukan mempersempit cara berpikir mereka.
Ketiga, libatkan peran keluarga dan lingkungan sekolah secara aktif. Pendidikan agama tidak akan pernah berhasil jika hanya mengandalkan guru. Dibutuhkan ekosistem yang mendukung—mulai dari orang tua, teman sebaya, hingga suasana sekolah yang menumbuhkan nilai-nilai keislaman secara alami. John Dewey, seorang filsuf pendidikan dari Amerika, menyatakan bahwa “Education is not preparation for life; education is life itself.” Maka pendidikan agama bukan pelajaran tambahan, tapi seharusnya menjadi napas dalam kehidupan sekolah dan masyarakat.
Sebagai seorang pendidik dan peneliti, saya menilai kondisi saat ini mengkhawatirkan. Kita sedang mencetak generasi yang tahu banyak hal tentang Islam, tapi tidak mencerminkan Islam dalam sikap dan perilakunya. Mereka tahu bahwa ghibah itu dosa, tapi tetap dilakukan. Mereka tahu bahwa jujur itu mulia, tapi tetap memilih jalan pintas.
Jika ini terus dibiarkan, kita akan menghasilkan generasi muslim yang “pintar beragama tapi gagal menjadi pribadi beragama.” Pendidikan agama harus kembali kepada misinya: membentuk manusia yang sadar Tuhan, berakhlak, dan menjadi rahmat bagi sekitarnya. Bukan sekadar menjadi ahli debat agama, tapi jauh dari adab.
Wallahu A’lam bi ash-Showab.