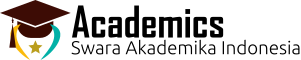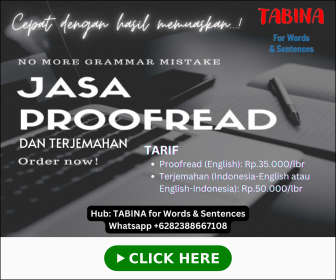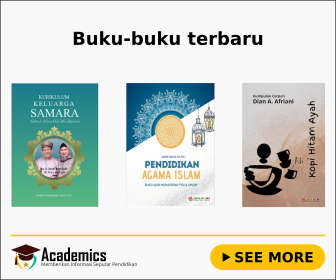ACADEMICS.web.id – Beberapa hari terakhir, ruang-ruang diskusi pendidikan—baik di warung kopi, seminar, maupun grup WhatsApp orang tua—diramaikan oleh kebijakan terbaru Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), yang menetapkan jam masuk sekolah pukul 06.00 WIB mulai tahun ajaran 2026/2027. Kebijakan ini ditegaskan melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 51/PA.03/Disdik, dan akan berlaku untuk semua jenjang: SD, SMP, hingga SMA.
Bagi masyarakat Jawa Barat, nama Dedi Mulyadi bukan asing. Sosok yang penuh semangat dan sering tampil dengan narasi lokalitas Sunda ini menyampaikan bahwa kebijakan masuk jam 06.00 pagi bukanlah hal baru. Ia pernah menerapkannya ketika menjadi Bupati Purwakarta. Alasannya pun tampak sederhana dan rasional: efisiensi rutinitas keluarga. “Orang tua bisa berangkat bersama anaknya, mengantar ke sekolah dulu baru ke kantor. Ini kan efektif,” ujarnya.
Sekilas, alasan tersebut memang terdengar menarik. Siapa yang tidak ingin efisien? Siapa yang tidak ingin kebersamaan keluarga dijaga bahkan sedari waktu pagi? Namun, sebagai pendidik dan pengamat sosial, saya merasa perlu untuk mengajak kita semua—terutama para pengambil kebijakan—untuk melihat ini bukan semata dari sisi “praktis administratif,” tetapi dari kacamata yang lebih dalam: bagaimana sebuah kebijakan menyentuh realitas dan memuliakan kemanusiaan.
Saya tidak sedang membantah nilai-nilai luhur bangun pagi. Bahkan dalam Islam, waktu subuh hingga terbitnya matahari adalah saat yang penuh keberkahan. Dalam banyak hadits, Rasulullah SAW mendoakan keberkahan bagi umatnya yang bangun pagi. Bahkan dalam Surah al-Fajr, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Tapi nilai spiritual ini tidak bisa otomatis dijadikan dasar kebijakan struktural untuk jutaan siswa dari berbagai latar belakang sosial dan geografis yang sangat berbeda. Sekolah-sekolah yang menjadi target kebijakan tersebut bukan pesantren, itu semua sekolah umum. Dan dari aspek rumah tangga, tidak semua keluarga hidup dalam ritme yang seragam.
Siswa di daerah urban mungkin masih bisa menyesuaikan diri. Tapi bagaimana dengan siswa di pelosok desa yang harus menempuh perjalanan panjang dengan transportasi terbatas? Bagaimana dengan anak-anak yang tinggal bersama neneknya karena orang tuanya bekerja di luar kota? Dan bagaimana dengan guru-guru yang harus lebih pagi menyiapkan materi pelajaran, berangkat dalam gelap, dan tetap dituntut mengajar dengan semangat penuh?
Kita harus ingat, pendidikan tidak bisa diseragamkan hanya karena niatnya baik. Niat baik tidak selalu menjamin hasil baik, apalagi jika tidak diikuti dengan analisis yang matang.
Mendorong anak ke sekolah lebih pagi bukan otomatis berarti mereka akan lebih disiplin atau lebih cerdas. Beberapa studi neurologi dan psikologi pendidikan justru menunjukkan bahwa konsentrasi anak usia sekolah baru optimal setelah tubuhnya cukup istirahat dan mendapatkan asupan gizi yang baik. Anak yang datang terlalu pagi, dengan mata masih sembab dan perut belum terisi, bukanlah anak yang siap belajar—melainkan anak yang dipaksa tampak disiplin di hadapan absen dan tata tertib.
Seorang ahli pendidikan asal Finlandia, Pasi Sahlberg, pernah berkata, “More hours in school do not always mean more learning. It’s not about quantity, but the quality of the school day.” Maka jika yang ingin kita bangun adalah disiplin, mulailah dari konsistensi pendekatan, bukan sekadar memajukan jam.
Di beberapa negara maju seperti Finlandia dan Kanada, justru jam masuk sekolah dimulai pukul 8 atau 9 pagi, agar anak-anak benar-benar siap secara fisik dan mental. Kita tentu tidak sedang meniru mereka secara buta, tetapi jika mereka yang sudah jauh maju saja menjaga ritme alami anak, mengapa kita justru mempercepat ritme tanpa menyiapkan sistem pendukung yang cukup?
Saya tidak mengatakan bahwa KDM salah niat. Saya percaya ia ingin yang terbaik bagi masyarakat Jawa Barat. Namun, kebijakan publik dalam dunia pendidikan bukan hanya soal visi dan keberanian, tapi juga tentang proses mendengarkan. Dengarkan guru, dengarkan orang tua, dan—terpenting—dengarkan suara batin anak-anak kita. Mereka mungkin belum bisa menulis opini, tapi tubuh dan ekspresi mereka cukup fasih bicara tentang ketidaknyamanan yang dipaksakan.
Dalam satu fragmen pemikirannya, Ali bin Abi Thalib RA pernah menasihatkan, “Jangan kamu didik anakmu dengan cara hidupmu, karena mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda denganmu.” Sebuah kalimat pendek, tapi sarat makna. Dunia anak sekarang bukanlah dunia kita dua dekade lalu. Mereka tumbuh dengan tantangan, kebutuhan, dan ritme yang berbeda. Maka kebijakan pendidikan pun harus kontekstual, bukan hanya sentimental.
Kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 mungkin tampak rapi di atas kertas. Tapi pendidikan bukan spreadsheet. Ia adalah interaksi antarjiwa. Maka ketika kita membuat kebijakan, pastikan ia tidak sekadar menjawab efisiensi birokrasi, tapi menjamin kelangsungan semangat belajar, kesehatan mental, dan integritas proses pendidikan.
Sebab, bila sekolah kehilangan ruh kemanusiaannya hanya karena ingin mengejar kesan tertib dan serentak, kita sedang membangun sistem yang kaku, bukan komunitas belajar yang hidup.
Wallahu A’lam bi ash-Showab.@