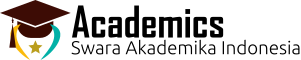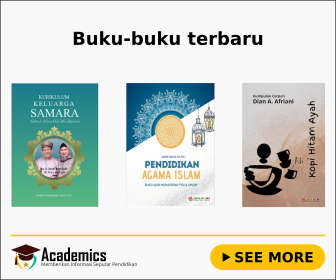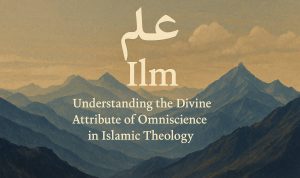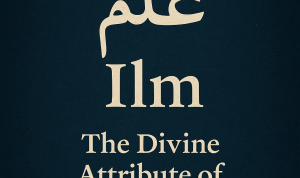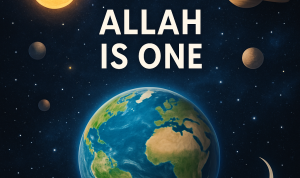ACADEMICS.web.id – Pertanyaan tentang eksistensi Tuhan selalu menjadi perdebatan klasik yang tidak lekang oleh zaman. Bagi sebagian orang, kehadiran Tuhan adalah kebenaran mutlak yang tak perlu dipertanyakan. Namun bagi sebagian lain, terutama mereka yang terjebak dalam gelombang rasionalisme dan sains modern, pertanyaan itu bertransformasi menjadi gugatan. “Apakah Tuhan benar-benar ada?”
Dari gugatan itulah lahir ateisme, sebuah pandangan yang menafikan eksistensi Tuhan. Ateisme bukan sekadar menolak agama, tapi lebih dalam dari itu, ia menolak kemungkinan adanya realitas di luar alam semesta yang bisa disebut dengan Tuhan. Ia adalah keangkuhan akal yang mencoba menjadikan dirinya pusat segala ukuran, seolah dunia dan manusia cukup dijelaskan tanpa perlu melibatkan Yang Maha Kuasa.
Namun jauh sebelum para filsuf Eropa menuliskannya dalam naskah-naskah modern, Al-Qur’an telah lebih dulu merespons cara berpikir semacam itu dengan pendekatan yang sangat menarik. Ia tidak langsung menghakimi, tetapi mengajak berpikir. Ia tidak menutup pintu logika, justru membuka ruang bagi rasio untuk menemukan kebenaran lewat perenungan yang jujur.
Dalam bahasa yang elegan dan argumentatif, Al-Qur’an menuntun manusia memahami realitas hidup, mati, dan kehidupan sesudahnya. Dalam bingkai itulah kita menemukan betapa Al-Qur’an bukan hanya kitab wahyu, tetapi juga kitab logika ilahiah yang menjawab ateisme dengan kekuatan nalar.
Dunia: Antara Keindahan dan Tipu Daya
Al-Qur’an berulang kali mengingatkan manusia bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, dan kesenangan yang menipu. Dalam Surah al-An‘am: 32, Allah berfirman bahwa “kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa.”
Ayat ini bukan larangan untuk mencintai dunia, tetapi peringatan agar manusia tidak tertipu olehnya. Dunia memang indah, tapi kekal. Seperti panggung teater yang megah di awal, namun pada akhirnya tirainya akan turun, dan penonton harus pulang meninggalkannya melompong.
Dari ketidaksadaran seperti inilah ateisme modern tumbuh. Dunia dianggap satu-satunya realitas. Manusia dipandang sebagai makhluk biologis yang hidup untuk memenuhi naluri, menikmati waktu singkatnya, lalu hilang. Akibatnya, nilai hidup direduksi menjadi sekadar ukuran materi.
Al-Qur’an mengajak manusia berpikir lebih dalam. Dalam Surah Yunus: 24, kehidupan dunia diibaratkan seperti hujan yang menumbuhkan tanaman hijau yang memukau mata. Saat manusia mulai merasa berkuasa atas hasilnya, tiba-tiba datanglah kehancuran, dan semuanya lenyap. Analogi ini begitu filosofis. Dunia bukan musuh manusia, tapi refleksi tentang kefanaan. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, akan tenggelam dalam kehampaan. Sebaliknya, siapa yang menjadikannya sarana, akan menemukan makna.
Kematian: Gerbang, Bukan Akhir
Salah satu argumen klasik kaum ateis adalah penolakan terhadap kehidupan sesudah mati. Menurut mereka, kematian adalah akhir dari segalanya. Tidak ada kebangkitan, tidak ada perhitungan amal, tidak ada kehidupan setelah kehidupan.
Namun Al-Qur’an membantahnya dengan logika yang tajam dan sederhana. Dalam Surah al-Isra’: 49–51, Allah mengutip sindiran kaum kafir yang berkata, “Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan hancur luluh, kami akan dibangkitkan kembali?” Lalu Allah menjawab, “Katakanlah, yang akan menghidupkan kamu adalah Tuhan yang menciptakan kamu pertama kali.”
Logika ini luar biasa kuat. Jika manusia bisa diciptakan dari ketiadaan, mengapa kebangkitannya setelah mati dianggap mustahil? Menghidupkan yang sudah pernah ada tentu lebih mudah daripada menciptakan yang belum ada sama sekali.
Al-Qur’an juga memberikan contoh empiris yang dapat dirasakan oleh akal manusia: bumi yang mati kembali hidup setelah turunnya hujan. Dalam Fushshilat: 39, Allah menyebut kebangkitan manusia kelak serupa dengan kehidupan bumi yang gersang lalu menghijau. Alam menjadi saksi logis atas kekuasaan Tuhan.
Akal: Jalan Menuju Iman
Akal dan iman bukanlah dua kutub yang berseberangan. Dalam perspektif Al-Qur’an, keduanya adalah sahabat yang saling meneguhkan. Ateisme lahir bukan karena manusia terlalu rasional, tetapi karena ia memisahkan rasionalitas dari moralitas.
Ketika kaum kafir menantang Rasulullah dengan membawa tulang belulang yang lapuk dan berkata, “Siapa yang bisa menghidupkan ini setelah hancur?”, Allah menjawab dalam Yasin: 79–83, bahwa yang menghidupkan tulang itu adalah Dzat yang pertama kali menciptakannya.
Di sini Al-Qur’an menggunakan pendekatan logika sederhana tapi dalam:
Jika engkau percaya bahwa manusia dulu tidak ada, lalu menjadi ada, mengapa engkau menolak kemungkinan bahwa yang menciptakan pertama kali juga mampu mengulanginya?
Ini bukan sekadar argumen teologis, melainkan reasoning pattern yang menegaskan bahwa penolakan terhadap Tuhan justru bertentangan dengan logika yang sehat. Karena menolak Tuhan berarti menolak sebab pertama dari segala sebab.
Ketika Kebenaran Tidak Lagi Dipercaya
Ateisme bukan hanya persoalan intelektual, tapi juga krisis spiritual. Ketika manusia kehilangan keyakinan kepada Tuhan, ia bukan hanya kehilangan arah berpikir, tetapi juga arah moral.
Al-Qur’an menggambarkan keadaan ini dalam Surah al-Ankabut: 23: “Orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan-Nya, mereka berputus asa dari rahmat-Ku, dan bagi mereka azab yang pedih.”
Yang hilang dari hati orang ateis bukan sekadar keyakinan, tapi harapan. Tanpa iman kepada Tuhan, hidup terasa seperti perjalanan tanpa tujuan. Kematian menjadi ketakutan yang tidak terjawab, dan kehidupan menjadi kesibukan tanpa makna.
Dalam Surah al-Kahfi: 104–105, Allah menyebut mereka sebagai “orang-orang yang perbuatannya sia-sia, padahal mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya.” Ini adalah ironi eksistensial. Kebaikan tanpa orientasi kepada Tuhan hanyalah bayangan moral tanpa jiwa. Ia tampak indah, tapi kosong dari nilai akhirat.
Akal manusia bisa menemukan kebaikan, tetapi hanya wahyu yang memberi makna. Di sinilah letak keunggulan Al-Qur’an: ia tidak menafikan akal, tetapi menempatkannya di bawah bimbingan nilai ilahiah.
Surga dan Neraka: Keadilan yang Tak Terhindarkan
Bagi sebagian orang, konsep surga dan neraka dianggap mitos religius. Tapi bagi Al-Qur’an, keduanya adalah puncak keadilan Tuhan.
Dalam Surah Thaha: 74–76, Allah membedakan dua kelompok manusia:
yang datang dengan dosa dan kesombongan akan kekal dalam azab;
sementara yang datang dengan iman dan amal saleh akan memperoleh surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya.
Surga dan neraka bukan sekadar simbol pahala dan hukuman, melainkan representasi dari hukum sebab-akibat spiritual. Jika dunia memiliki konsekuensi logis atas setiap tindakan fisik, maka alam akhirat adalah konsekuensi moral atas setiap tindakan batin.
Tanpa kepercayaan pada hari pembalasan, moralitas manusia kehilangan dasar objektifnya. Segala sesuatu menjadi relatif, tergantung kepentingan dan kesenangan pribadi. Di sinilah letak bahaya terbesar ateisme: bukan hanya menolak Tuhan, tapi juga meniadakan ukuran benar dan salah.
Antara Akal dan Iman: Menemukan Keseimbangan
Al-Qur’an tidak pernah memusuhi akal. Ia justru menyeru manusia untuk berpikir, meneliti, dan merenung. Namun ia juga memperingatkan bahwa akal tanpa iman ibarat kompas tanpa arah utara. Ia bisa pintar, tapi tidak bijak; bisa tahu banyak hal, tapi tidak tahu ke mana harus melangkah.
Ateisme modern adalah contoh bagaimana akal yang tercerabut dari iman akhirnya melahirkan kehampaan eksistensial. Manusia menciptakan teknologi canggih, tetapi kehilangan ketenangan batin. Membangun peradaban besar, namun kehilangan nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam konteks ini, iman bukan sekadar keyakinan dogmatis, tetapi penuntun etis bagi rasionalitas. Al-Qur’an mengajarkan bahwa berpikir adalah ibadah, dan beriman adalah bentuk tertinggi dari kesadaran intelektual.
Di dunia modern saat ini, ateisme tidak lagi berdiri di atas logika murni, tetapi sering kali berakar pada kekecewaan terhadap agama yang disalahgunakan. Di banyak tempat, agama dijadikan alat kekuasaan, bukan sarana pembebasan. Maka tak heran, sebagian orang lari dari agama, bukan karena benci pada Tuhan, tapi karena tidak menemukan Tuhan dalam perilaku orang beragama.
Al-Qur’an menyadari hal ini. Ia tidak memaksa manusia untuk beriman secara buta, tetapi menuntut kejujuran berpikir. Tuhan tidak meminta manusia berhenti berpikir, justru menginginkan manusia berpikir dengan benar. Karena berpikir tanpa hati akan menyesatkan, dan beragama tanpa akal akan membutakan.
Pada akhirnya, perdebatan antara ateisme dan teisme bukanlah sekadar tentang ada atau tidaknya Tuhan, tetapi tentang makna menjadi manusia.
Apakah manusia hanya kumpulan sel yang berfikir, ataukah makhluk spiritual yang mencari kebenaran abadi?
Al-Qur’an menegaskan bahwa iman dan akal bukan dua dunia yang bertentangan. Iman tanpa akal akan kaku, akal tanpa iman akan liar. Keduanya harus berjalan beriringan agar manusia tidak tersesat di tengah peradaban yang gemerlap tapi gersang makna.
Karena sesungguhnya, kebangkitan yang paling hakiki bukanlah saat manusia keluar dari kubur, melainkan ketika akalnya bangkit dari tidur panjang kesombongan. Wallahu A‘lam bi al-Shawab.@

Sofiandi, Lc., MHI., Ph.D
Guru PAI di Bakti Mulya 400, juga tercatat sebagai Research Fellow di beberapa lembaga seperti Fath Institute for Islamic Research Jakarta, IRDAK Institute of Singapore, Asia-Pacific Journal on Religion and Society, Institute for Southeast Asian Islamic Studies, Islamic Linkage for Southeast Asia, Anggota Dewan Masjid Indonesia, Ketua Dewan Pembina Badan Koordinasi Muballigh Indonesia Prov. Kepri, Anggota ICMI Prov. Kepri, Pembina Ikatan Wartawan Online Indonesia Prov. Kepri, dan aktif menulis mengenai isu-isu pendidikan selain politik, sosial, dan ekonomi.