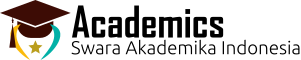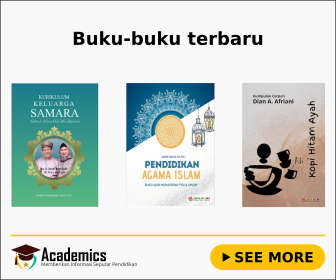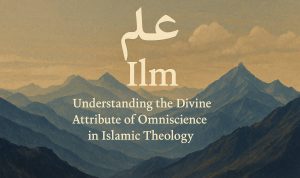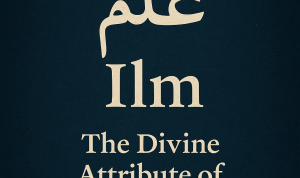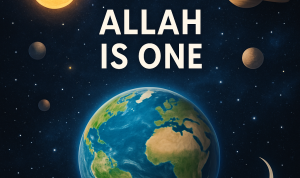ACADEMICS.web.id – Pemahaman tentang hakikat hidup senantiasa menjadi medan refleksi yang tidak pernah lekang oleh waktu. Dalam perspektif eksistensial maupun spiritual, manusia dituntut untuk membedakan secara jernih antara tujuan hidup dan makna hidup—dua konsep yang tampak serupa namun memiliki kedalaman yang berbeda secara fundamental. Tujuan hidup merujuk pada apa yang ingin dicapai seseorang, sedangkan makna hidup berkaitan dengan alasan mengapa kehidupan itu sendiri berharga. Tanpa tujuan, hidup kehilangan arah; namun tanpa makna, tujuan yang dicapai hanya menjadi prestasi kosong yang tidak meninggalkan resonansi batin.
Makna hidup tidak lahir dari ruang hampa; ia merupakan hasil perjumpaan antara nilai utama yang diyakini seseorang dengan pengalamannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang bersusah payah mencapai sebuah capaian, makna hidup berfungsi sebagai energi intrinsik yang membuat proses itu tetap bernilai, bahkan ketika harus menghadapi kesulitan. Makna hidup yang kuat memberikan fondasi spiritual dan emosional yang membuat manusia mampu bertahan dalam penderitaan alih-alih menghindarinya. Dengan kata lain, makna hidup menjadi kompas batin yang mengarahkan tindakan, pilihan, dan respons individu terhadap dinamika kehidupan.
Untuk menemukan makna tersebut, refleksi diri menjadi syarat mutlak. Pertanyaan-pertanyaan sederhana namun mendalam—seperti apa hal terbaik yang disyukuri hari ini, apakah tindakan yang dilakukan memberikan manfaat bagi orang lain, atau apakah hari ini layak ditinggalkan jika esok tidak lagi tiba—menjadi pintu masuk bagi pemahaman tentang apa yang benar-benar bernilai. Makna hidup yang autentik biasanya menunjukkan konsistensi jangka panjang, melampaui kepentingan diri sendiri, serta menguatkan hubungan spiritual seseorang dengan Tuhan.
Berbeda dengan makna, tujuan hidup mengandung sifat yang lebih operasional. Ia bersifat terukur, konkret, dan dapat direncanakan. Di sinilah prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) memainkan peran penting. Sebuah tujuan yang jelas dan realistis tidak hanya memudahkan individu untuk membuat peta perjalanan hidup, tetapi juga memastikan bahwa energi dan waktu yang diinvestasikan terarah pada sesuatu yang relevan.
Namun tujuan hidup tidak berdiri sendiri; ia perlu dilekatkan pada makna hidup agar tidak sekadar menjadi daftar rencana tanpa jiwa. Misalnya, seseorang yang ingin menulis sebuah buku dalam waktu dua tahun tentu akan lebih konsisten jika tujuan tersebut didorong oleh makna yang lebih besar—misalnya keinginan untuk memberi manfaat bagi masyarakat atau bentuk pengabdian kepada Tuhan. Dengan demikian, tujuan hidup memperoleh legitimasi moral dan spiritual.
Hubungan antara makna dan tujuan hidup dapat diibaratkan seperti perjalanan dan alasan perjalanan itu dilakukan. Tujuan memberikan alamat yang dituju, sedangkan makna memberikan justifikasi mengapa perjalanan itu penting. Begitu pula dalam analogi bangunan rumah: tujuan menentukan bentuk rumah yang ingin diwujudkan, sedangkan makna menjelaskan untuk apa rumah itu dibangun. Tanpa tujuan, rumah tidak akan selesai; namun tanpa makna, rumah dapat berdiri megah tetapi kosong dari nilai. Keduanya membentuk struktur kehidupan yang utuh. Tujuan mendisiplinkan tindakan, sedangkan makna menumbuhkan ketenangan batin dan rasa utuh. Perpaduan keduanya melahirkan kehidupan yang tidak hanya produktif, tetapi juga bermakna—sebuah kehidupan yang tidak berhenti pada pencapaian lahiriah, tetapi meresap hingga ke lapis terdalam spiritualitas manusia.
Pemaknaan terhadap hidup tidak dapat dilepaskan dari fondasi ajaran Islam yang memandang kehidupan sebagai amanah (trust) dan ladang pengabdian. Al-Qur’an mengingatkan manusia bahwa eksistensinya di dunia memiliki tujuan yang luhur, sebagaimana firman Allah: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat [51]: 56). Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama keberadaan manusia bukan hanya mencapai target duniawi, tetapi meletakkan setiap usaha dalam kerangka ibadah yang menyeluruh—baik dalam bentuk ritual, moral, maupun kontribusi sosial.
Lebih jauh, makna hidup dalam perspektif Islam ditautkan dengan kemampuan seseorang untuk memaknai peristiwa dan penderitaan sebagai bagian dari proses penyucian jiwa. Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa “Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, seluruh urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, dan itu juga baik baginya.” (HR. Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa makna hidup yang matang tidak ditentukan oleh ada-tidaknya kesulitan, tetapi oleh kemampuan mengintegrasikan syukur dan sabar dalam setiap fase kehidupan.
Makna hidup juga tidak bersifat individualistis. Islam menegaskan pentingnya memberikan manfaat sebagai ukuran kemuliaan seseorang. Nabi SAW bersabda, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad). Dengan demikian, makna hidup yang sejati adalah makna yang melampaui kepentingan personal, bergerak menuju kontribusi bagi masyarakat dan penguatan nilai-nilai ketuhanan.
Refleksi mengenai makna dan tujuan hidup semakin kaya ketika ditautkan dengan khazanah pemikiran ulama klasik. Imam al-Ghazali, misalnya, memandang kehidupan manusia sebagai perjalanan ruh menuju Allah. Dalam Ihya’ Ulum al-Din, ia menekankan bahwa makna hidup hanya dapat diraih apabila seseorang mampu mensinergikan potensi akal, hati, dan amal. Menurut beliau, manusia akan menemukan makna sejati ketika orientasi tindakannya bukan pada dunia semata, tetapi pada penyucian jiwa (tazkiyatun nafs) dan kedekatan dengan Allah. Maka, setiap tujuan hidup yang tidak memperkuat dimensi ruhani akan kehilangan esensi terdalamnya.
Sementara itu, Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa hidup adalah ruang pendidikan ilahi. Dalam Madarij as-Salikin, ia menjelaskan bahwa manusia memperoleh makna melalui tiga pilar spiritual: ma’rifah (pengenalan kepada Allah), mahabbah (cinta Ilahi), dan khidmah (pengabdian). Baginya, tujuan hidup bukan hanya pencapaian lahiriah, tetapi perjalanan bertahap menuju kualitas jiwa yang semakin halus. Ibn Qayyim juga menekankan bahwa penderitaan merupakan salah satu instrumen tarbiyah Allah—suatu cara untuk mengangkat derajat dan memperdalam makna eksistensi seorang hamba.
Dalam wacana pemikiran kontemporer, tokoh-tokoh seperti Syed Muhammad Naquib al-Attas menyoroti bahwa krisis makna hidup pada manusia modern muncul akibat hilangnya adab (loss of adab), yakni hilangnya penempatan sesuatu pada tempat yang benar. Al-Attas menekankan bahwa makna hidup tidak dapat ditemukan kecuali jika seseorang memahami hakikat dirinya, hakikat ilmu, dan hakikat tujuan penciptaannya. Dalam kerangka ini, tujuan hidup bukan sekadar target temporal, tetapi bagian dari upaya menegakkan tatanan moral dan spiritual dalam diri maupun masyarakat.
Pemikiran para ulama ini memperkuat tesis bahwa makna hidup bersifat multidimensional: ia mencakup dimensi spiritual, rasional, moral, dan sosial. Ketika seseorang mampu menautkan seluruh dimensi ini dalam suatu integrasi yang harmonis, maka lahirlah kehidupan yang bukan saja terarah, tetapi juga bersifat transformatif—mengubah diri, memberi manfaat bagi sesama, dan mendekatkan diri kepada Allah.
Diskusi mengenai dimensi makna dan tujuan hidup ini akan semakin menemukan kedalamannya ketika dianalisis melalui lensa para pemikir besar Islam yang menawarkan pendekatan metafisik, rasional, dan etis yang berbeda namun saling melengkapi.
Ibn ‘Arabi, tokoh sufi besar dalam tradisi Islam, menempatkan makna hidup dalam kerangka ma’rifah—pengenalan mendalam terhadap Realitas Ilahi. Menurutnya, manusia adalah cermin bagi tajalli (manifestasi) sifat-sifat Tuhan. Karena itu, makna hidup tidak hanya ditemukan melalui perjalanan lahiriah, melainkan melalui penyingkapan batin yang membuat seseorang menyadari bahwa seluruh keberadaannya adalah bagian dari wujud yang satu. Dalam pandangannya, tujuan hidup bukanlah sekadar mencapai sesuatu di dunia, tetapi menyadari dan menghayati kehadiran Ilahi dalam setiap momen kehidupan. Perspektif ini memperluas pengertian makna hidup dari sekadar refleksi rasional menjadi pengalaman spiritual yang transformasional.
Fakhr al-Din al-Razi, seorang teolog dan mufassir rasionalis, menawarkan pendekatan yang lebih epistemologis. Dalam karya-karyanya, ia sering menekankan bahwa manusia diciptakan dengan akal sebagai sarana untuk memahami tanda-tanda Allah di alam semesta. Al-Razi menafsirkan tujuan hidup sebagai proses berkesinambungan untuk mengenali hikmah di balik ciptaan serta menselaraskan diri dengan petunjuk Ilahi melalui ilmu dan amal. Baginya, makna hidup diperoleh melalui integrasi antara pencarian intelektual dan penguatan spiritual. Perspektif ini menunjukkan bahwa akal dan wahyu bukan dua kutub yang berlawanan, tetapi dua instrumen yang saling memperkaya dalam membantu manusia memahami arah hidupnya.
Tariq Ramadan, sebagai pemikir Muslim modern, melihat makna hidup dalam konteks manusia kontemporer yang berhadapan dengan kompleksitas globalisasi, teknologi, dan pluralitas. Ramadan menekankan konsep al-fann al-‘aysh—seni untuk hidup bermakna. Ia menyatakan bahwa tujuan hidup seorang Muslim modern tidak cukup dengan kesalehan pribadi, tetapi harus diwujudkan dalam tanggung jawab sosial, keadilan, dan kontribusi aktif untuk dunia yang lebih manusiawi. Pandangan ini menggeser makna hidup dari ruang batin semata menuju keterlibatan etis dalam masyarakat. Dengan demikian, makna hidup menjadi jembatan antara spiritualitas dan aksi sosial.
Ketiga perspektif ini—metafisika Ibn ‘Arabi, rasionalisme al-Razi, dan etika sosial Tariq Ramadan—membentuk satu kesatuan yang memperkaya pemahaman kita tentang hakikat hidup. Mereka menunjukkan bahwa makna dan tujuan tidak dapat dipahami secara tunggal; keduanya merupakan hasil dialog antara batin, akal, dan realitas sosial. Dalam kerangka pemikiran ini, hidup menjadi perjalanan yang tidak hanya diarahkan kepada Allah, tetapi juga untuk menghadirkan nilai-nilai Ilahi dalam kehidupan manusia
Pada akhirnya, upaya memahami hakikat hidup bukan sekadar latihan intelektual, tetapi juga perjalanan spiritual dan moral. Makna dan tujuan hidup harus dirawat melalui muhasabah, dialog batin, dan tindakan yang konsisten. Keduanya menawarkan arah dan kedalaman, sehingga manusia dapat menjalani hidup yang bukan hanya penuh capaian, tetapi juga penuh kebermaknaan. Dengan fondasi tersebut, seseorang bukan sekadar hidup—ia tumbuh, memberi manfaat, dan mendekat kepada Sang Pencipta. Wallahu a’lam bi Ashowab @
Sofiandi, Lc., MHI., Ph.D adalah Research Fellow di Fath Institute for Islamic Research, di IRDAK Institute of Singapore, di Institute for Southeast Asian Islamic Studies (ISAIS), Anggota Dewan Masjid Indonesia Kota Batam, Anggota ICMI Prov. Kepri, Sekretaris Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Prov. Kepri, guru PAI Bakti Mulya 400, dan dosen di beberapa kampus yang juga aktif menulis mengenai isu-isu pendidikan selain politik, sosial, dan ekonomi.